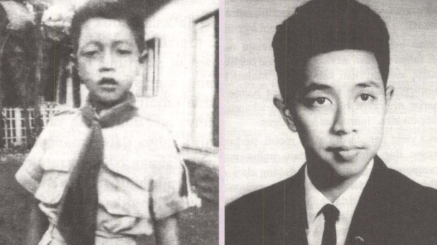Menteri Pendidikan Masa Jabatan 26 Oktober 1999 – 22 Juli 2001
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
(Depdikbud) diubah namanya menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Yahya A.
Muhaimin diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional di bawah
pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid berdasar Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999.
Masa jabatan Yahya A. Muhaimin berlangsung sejak tanggal 26 Oktober 1999 hingga 22 Juli 2001.
Yahya A. Muhaimin berasal dari keluarga yang taat pada agama. Kakeknya, Haji Machfudz, seorang
saudagar dan aktivis pergerakan dengan bergabung dalam Syarekat Islam. H. Machfudz bersama dengan
temannya mendirikan madrasah Ta’allumul Huda, suatu perguruan Islam yang pertama di Bumiayu, pada
tahun 1917.
Ayah Yahya A. Muhaimin, Haji Abdul Muhaimin, merupakan seorang pedagang kaya yang memperhatikan pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum kepada anak-anaknya. Madrasah Ta’alumul Huda yang didirikan oleh kakeknya tetap dibantu oleh ayah Yahya A. Muhaimin. lbu Yahya A. Muhaimin, Hajjah Zubaidah, sehari-hari membantu usaha suaminya. Pada masa itu Zubaidah termasuk wanita yang maju. Di samping dididik agama oleh orang tuanya, ia juga dimasukan ke sekolah umum “Kartini”. Yahya A. Muhaimin dilahirkan di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, pada tanggal 17 Mei 1943. Latar
belakang keluarga mempengaruhi perjalanan pendidikannya. Pada umur sekolah dasar ia mengikuti
dua sekolah, yaitu Madrasah lbtidaiyah (MI) Ta’allumul Huda dan Sekolah Rakyat 5 (SR-5) di Kota
Bumi Ayu, dan lulus pada tahun 1956. Kemudian ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Islam (setingkat
Sekolah Menengah Pertama/SMP) di lembaga pendidikan Ta’alamul Huda dan lulus pada tahun 1959.
Setelah menyelesaikan SMP ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi berpindah-pindah
sekolah, yaitu SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, SMA Negeri di Tegal, SMA Negeri I Purwokerto,
SMA Muhammadiyah Purwokerta, dan lulus di SMA Negeri I Purwokerto. Ketika sekolah di SMA
Negeri I Purwokerto ia mengikuti program The American Field Service International Scholarship
(AFSIS), Amerika Serikat (AS), selama setahun (1962-1963).
Sepulang dari AS dan menyelesaikan SMA, Yahya melanjutkan kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM)
pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Sosial Politik (Sospol), tetapi kemudian pindah ke Jurusan
Hubungan lnternasional. Selain kuliah di UGM ia juga kuliah di lnstitut Agama Islam Negeri (lAIN)
Yogyakarta Jurusan Perbandingan Agama, tetapi tidak selesai. Yahya menyelesaikan kuliahnya di UGM
Pada tahun 1971 dan kemudian diangkat menjadi dosen di almamaternya.Yahya melanjutkan studi ke luar
negeri di The Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) yang diselesaikannya pada tahun 1982 dengan
memperoleh gelar Ph.D di bidang Political Development and Comparative Politics dan Studi Kawasan
Asia dengan disertasi berjudul Indonesian Economic Policy, 1950-1980: the Politics of Client Businessmen.
Selama menjadi dosen di UGM Yahya memegang jabatan struktural di kampus, yaitu pengelola
Program S2 Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (Fisipol) UGM (1982-1984) serta Kepala Pusat Studi
Keamanan dan Perdamaian UGM ( 1996-1999). Pengalaman jabatan tersebut mengantarkannya menjadi
Ketua Jurusan Hubungan lnternasional Fisipol UGM, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fisipol UGM;
Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington
DC, Amerika Serikat, serta Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
MENJADI AKTIVIS
Selain menjadi seorang akademisi di kampus, Yahya A. Muhaimin juga seorang aktivis organisasi kemasyarakatan hingga sekarang, antaralain Persyarekatan Muhammadiyah. Kehidupan sebagai aktivis dijalaninya sejak sekolah hingga menjadi mahasiswa. Pengalaman sebagai aktivis inilah yang
kemudian membuat Yahya memiliki banyak pergaulan dengan berbagai kalangan, khususnya para
aktivis kegiatan keagamaan. Ketika duduk di bangku Sekolah Dasar, Yahya aktif dalam kegiatan kepanduan: “Pandu Islam”. Ketika itu banyak organisasi kemasyarakatan memiliki organisasi pandu dengan nama tersendiri, seperti Pandu Islam, Pandu Rakyat, Pandu Ansor, Pandu Hizbul Wathen, Pandu Siap, dan Kepanduan Bangsa Indonesia. Organisasi itu sangat bermanfaat bagi pembinaan generasi muda sebagai sarana pelatihan kepemimpinan. Organisasi-organisasi kepanduan tersebut kemudian dibubarkan oleh pemerintah dan secara organisasi dilebur ke dalam satu wadah bernama Praja Muda Karana (Pramuka). Ketika aktif di kepanduan, Yahya pernah memperoleh suatu kegembiraan. Ia akan dikirim ke Filipina mewakili Pandu Islam Kabupaten Brebes untuk mengikuti Jambore. Akan tetapi rencana pergi ke
luar negeri itu tidak terlaksana. Orang tuanya tidak mengizinkan karena Yahya waktu itu masih siswa
SD dan masih kecil. Orang tuanya khawatir. Walaupun agak kecewa Yahya menuruti keinginan orang
tuanya. lbunya menasihati dan mengobati kekecewaan Yahya dengan mengatakan bahwa kelak suatu
saat Yahya akan bisa ke luar negeri. Nasihat orang tuanya itu kelak menjadi kenyataan ketika Yahya
sekolah di SMA lolos mengikuti program pertukaran siswa ke Amerika yang dikenal dengan program
The American Field Service International Scholarship (AFSIS) selama setahun ( 1962-1963).
Ketika menjadi mahasiswa, Yahya aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan lkatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). HMI adalah organisasi mahasiswa Islam yang didirikan pada tanggal
5 Februari 1947, organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia; bahkan merupakan
organisasi yang sangat berpengaruh di Indonesia karena para alumninya banyak memegang jabatan
strategis di pemerintahan. HMI merupakan organisasi independen dan tidak berada di bawah
struktur organisasi mana pun, sedangkan IMM adalah organisasi mahasiswa yang berada di bawah
Muhammadiyah. Pada saat aktif di HMI Yahya mendirikan Sospol English Club (SSB), suatu kelompok
studi mahasiswa yang membantu para mahasiswa di Sospol UGM mempelajari bahasa lnggris dan
sebagai sarana untuk merekrut mahasiswa menjadi anggota HMI.
Ia mendirikan SSB karena ia alumni AFSIS sehingga memiliki kemampuan berbahasa lnggris secara baik.
Yahya A. Muhaimin mengenal Muhammadiyah sejak kecil karena di kampung halamannya, Bumiayu,
sudah berdiri Cabang Muhammadiyah sejak sebelum ia lahir. Secara formal ia mengenal Muhammadiyah
ketika sekolah di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta dan kemudian pindah ke SMA Muhammadiyah
Purwokerto walaupun hanya satu kuartal. Di lingkungan keluarga pun ia mengenal Muhammadiyah karena ada anggota keluarganya yang aktif di Masyumi. Saat itu banyak orang Muhammadiyah yang aktif
di Masyumi, termasuk keluarga Yahya. Ia mengenal Muhammadiyah dengan lebih dekat ketika menjadi mahasiswa di UGM dan aktif sebagai pengurus IMM. Pada tahun 1985, sepulang dari Amerika Serikat setelah menyelasikan Doktor, Yahya masuk ke dalam jajaran Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ketika pertama kali menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah ia diangkat menjadi Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan. Setelah itu beberapa jabatan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dipegangnya, yaitu Wakil Ketua (1985-1990), Ketua (1990-1995), Pembina Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (1995-2000), dan pada tahun 2002 menjadi salah seorang Wali Amanah Lembaga Amil Zakat, lnfaq dan Shodaqoh.
Pada saat menjabat di Majelis Pendidikan Tinggi, pemikiran Yahya A. Muhaimin banyak berpengaruh
pada perubahan penting bagi persyarekatan Muhammadiyah. Gagasan-gagasan dan pemikiran itu
disampaikan dalam berbagai forum dan seminar. Pada saat Yahya A. Muhaimin menjabat di Persyarekatan
Muhammadiyah banyak didirikan pusat studi pada universitas-universitas Muhammadiyah. Hal yang
dianggap baru bagi pengembangan Universitas Muhammadyah saat itu adalah pendirian Fakultas
Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Baca Juga : Agung Wicaksono, S.Pd. M.Pd
AHLI MILITER DAN PERTAHANAN
Selain menjadi Menteri Pendidikan Nasional, Yahya A. Muhaimin juga dikenal sebagai pengamat politik
dan militer. Kedua bidang tersebut sesungguhnya secara pribadi merupakan bidang yang traumatis
baginya pada masa kecil. Hal itu disebabkan daerah kelahirannya di Bumiayu, Jawa Tengah, menjadi ajang
pertempuran antara TNI dan Darul Islam (DI). Yahya merupakan pengamat politik dan kemiliteran yang
konsisten menyandarkan pada jalur keilmiahan, sehingga semua tulisannya menjadi rujukan untuk bahan
penelitian para dosen lain.
Karya Yahya A. Muhaimin yang juga menjadi rujukan adalah Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi
Indonesia 1950-1980, yang bertolak dari disertasinya. Buku tersebut membahas perkembangan patron
client di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Ia menyebut bahwa hubungan patron-client lahir
sebagai konsekuensi pelaksanaan berbagai kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh pemerintah Indonesia
sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru? Buku tersebut juga berbicara tentang “perselingkuhan”
antara penguasa dan pengusaha sebagai dampak dari pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru. Pembangunan ekonomi sangat memerlukan semangat “kewiraswastaan”, yang pada umumnya mempunyai semangat kompetitif, kemandirian, serta independensi. Akan tetapi di Indonesia semangat itu tidak ditemukan; bahkan sebaliknya muncul pengusaha yang tumbuh karena topangan negara, yang disebut Yahya sebagi client businessmen ‘pengusaha klien’. Semakin banyak pengusaha asli atau pengusaha pribumi, tetapi kebanyakan di antara mereka pengusaha yang tumbuh dan besar berkat dukungan kalangan birokrasi dan interaksi yang sangat menarik. Yahya percaya bahwa ada hubungan yang bersifat kausal antara bentuk kebijaksanaan ekonomi dengan lahir dan berkembangnya pengusaha. Ia mencoba melihat bagaimana dan teknik apa yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha tersebut di dalam membina atau menjaga hubungan tersebut. Client businessmen adalah para pengusaha yang bekerja dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan. Para pengusaha mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik birokrasi dan mereka sangat tergantung kepada konsesi dan monopoli yang diberikan pemerintah. Mereka lahir di luar aparat birokrasi, tetapi biasanya masih termasuk ke dalam keluarga elit yang sedang berkuasa. Yahya mendefinisikan client businessmen sebagai “individu dan perusahaan yang bergantung kepada penguasa untuk dapat melakukan kegiatan bisnis”, sedangkan peran ekonominya dikatakannya lebih lanjut dengan “ketergantungan yang sifatnya menentukan kepada koneksi atau hubungan dengan pengusaha.” ltulah yang membedakan antara pengusaha klien dan pengusaha mandiri. Yahya menjelaskan bahwa perilaku client businessmen bisa mengakibatkan paham
“bapakisme”, seperti yang marak pada zaman Orde Baru dengan istilah “Asal Bapak Senang”. Negara
Pada tulisan yang lain birokrasi patrimonial merupakan lingkungan terbaik bagi tumbuh suburnya korupsi, karena korupsi banyak dilakukan dengan menggunakan kedok birokrasi. Para kapitalis semu terse but merupakan client businessmen. Mereka individu dan perusahaan yang bergantung pada penguasa-yang menjadi patron mereka-untuk dapat melakukan kegiatan bisnisnya. Praktik patron-klien telah berlangsung sejak Indonesia baru mengecap kemerdekaan. Atas kritik terse but buku Yahya A. Muhaimin disomasi oleh Probosutedjo, seorang pengusaha yang juga adik tiri Soeharto, karena merasa tersindir oleh buku terbitan LPeS tersebut. Probosutedjo memprotes keras dan menuduh Yahya melakukan penghinaan. Meskipun demikian protes Probosutedjo disampaikan dalam batas-batas kewajaran etis. Probosutedjo memberi penjelasan, bantahan, dan tuntutan kepada yang diprotes serta ancaman gugatan pengadilan. Yahya pun siap mempertanggungjawabkan bukunya “secara imiah”. Yahya memang tampak ‘terpukul’ oleh kasus ini dari segi non-ilmiah, tetapi solidaritas rekan-rekannya menjadi dukungan non-ilmiah yang dibutuhkannya. Pada 12 Juni 2012 di kantor Menteri Pendidikan Nasional, Jakarta, Yahya A. Muhaimin meluncurkan buku biografinya dengan judul Tiga Kota Satu Pengabdian. Dalam buku bersampul hijau tersebut mantan Menteri Pendidikan Nasional pada masa Presiden AbdurramanWahid dan Megawati Soekarnoputri ini menceritakan pengalamannya di bidang yang berbeda-beda, antara lain perjalanan akademisnya, jejak langkahnya sebagai pengajar dan ilmuwan pada dunia pendidikan, dan keberadaannya sebagai pengamat militer yang disegani di negara ini.Analisisnya mengenai peran militer pada masa Orde Baru membuat dirinya semakin dikenal, yang menyebut bahwa militer saat itu memegang peran amat strategis dalam pemerintahan dan politik.
Baca Juga : Daftar Menteri Pendidikan Indonesia
PROGRAM PADA AWAL REFORMASI
Setelah Pemilu tahun 1999 K.H . Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Rl dan Megawati
Soekarno Putri sebagai Wakil Presidennya. Kabinetnya bernama Kabinet Persatuan Nasional. Nama
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dan
kemudian diubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan Nasional dengan Dr. Yahya A. Muhaimin sebagai
menterinya. Dampak perubahan nama tersebut masalah kebudayaan tidak berada di bawah naungan
Kementerian Pendidikan, tetapi bergabung ke Departemen Pariwisata. Tugas sebagai Menteri Pendidikan Nasional tidak ringan karena negara berada di tengah gejolak perpolitikan yang kian panas, perekonomian yang makin memburuk, inflasi yang semakin membumbung,
gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak di mana-mana, pengangguran dan kemiskinan
semakin bertambah parah, serta kerusakan moral dan akhlak masyarakat semakin parah. Dalam kedaan
krisis demikian diperlukan seorang manajer pendidikan nasional yang tangguh, memiliki pengalaman
dan ilmu yang luas, serta keberanian melangkah dengan konsep-konsep yang nyata dan terarah.
Ketika dilantik menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada 26 Oktober 1999 Yahya melihat banyak
sekali masalah di bidang pendidikan Indonesia, yang sebagian di antaranya merupakan peninggalan
Orde Baru. Dalam suasana seperti itu tentu tidak mudah bagi seorang menteri melakukan pembenahan
secara menyeluruh dan bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Di antara masalah
masalah pendidikan pada masa itu sebagai berikut:
- Kecilnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 200 I, yang hanya 3,8% dari anggaran belanja negara (sekitar Rp II ,3 trilyun dari Rp 295 trilyun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN).
- Anggaran yang kecil itu ditambah dengan adanya krisis ekonomi dan keuangan yang serius
sehingga mengakibatkan kondisi lembaga pendidikan menjadi sangat memprihatinkan. Banyak
bangunan sekolah rusak, bahkan roboh, dan tidak dapat diperbaiki karena tidak ada dana yang cukup baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. - Tingkat kesejahteraan guru masih tetap rendah dan tidak sepadan dengan waktu dan tenaga
yang dikeluarkan; padahal pada masa itu biaya hidup sangat tinggi karena inflasi yang tinggi.
Oleh karena itu, untuk pertama kali dalam sejarah, para guru turun ke jalan melakukan
demonstrasi di banyak kota menuntut kesejahteraan. - Terjadi banyak tawuran antar pelajar atau antar mahasiswa akibat kondisi pendidikan yang
kacau. Pada tahun 1999 terjadi 257 kasus tawuran di ibukota yang mengakibatkan 35 pelajar
tewas, 204 pelajar luka, dan 478 kendaraan rusak. Pada tahun berikutnya Kakanwil Depdiknas
DKI Jakarta Alwi Nurdin mengatakan bahwa sebanyak 1.369 pelajar dari 1.685.084 SMP dan
SMA melakukan tawuran. Hal ini mengakibatkan 26 pelajar tewas, 56 pelajar luka berat, dan
109 pelajar luka ringan. - Adanya tindak kekerasan di Kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)
di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kekerasan fisik dilakukan mahasiswa senior terhadap
mahasiswa junior. Lektor Kepala STPDN lnu Kencana Syafei mengatakan bahwa di sekolah
calon pemimpin birokrat ini terdapat 50 kasus kekerasan, narkoba, dan pelecehan seksual. - Semakin merajalelanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan zat-zat adiktif lainnya.
Pemakai zat-zat terlarang tersebut, generasi muda, di antaranya para pelajar. Fenomena yang
seperti gunung es ini sulit diselesaikan. - Pergaulan bebas juga terjadi di kalangan generasi muda berupa hubungan seks di kalangan
pelajar, kehamilan di luar nikah, aborsi, pernikahan dini, dan peristiwa lain yang menyertainya. - Makin banyak gelar kesarjanaan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang
tidak memenuhi standar baku, semisal melalui jalan yang tidak benar. - Kualitas sumber daya manusia Indonesia (human development index/HDI) semakin jauh di
bawah negara-negara ASEAN. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada tahun
2001 berada pada peringkat 102 dari 162 negara. - Kualitas akademis rata-rata siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Indonesia masih rendah, terutama dalam hal membaca,
matematika, dan sains (IPA). - Masalah kurikulum pendidikan nasional juga belum terselesaikan, padahal kurikulum
merupakan roh dalam pendidikan.
Program kerja yang dilakukan oleh Yahya mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bidang
pendidikan. Masalah-masalah tersebut, menurut Yahya, secara sederhana dikelompokkan ke dalam (I)
masih rendahnya pemerataan pendidikan; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; serta (3)
masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta kemandirian di kalangan akademisi. Masalah yang berkaitan dengan perguruan tinggi adalah mutu yang rendah dibandingkan dengan negara negara lain . Pada tahun 1999 mutu pendidikan tinggi di Indonesia tidak termasuk ke dalam sepuluh besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Selandia Baru dan Australia. Sepuluh terbaik dunia bidang pendidikan meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Hongkong, Singapura, Australia, Cina, Thailand, Malaysia, dan Filipina. lnstitut Teknologi Bandung berada pada peringkat ke-21 , Universitas Indonesia ke-61, UGM ke-68, Universitas Diponegoro ke-73 , dan Universitas Airlangga ke-77. Oleh karena itu kemudian Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/u/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Human Development Report yang dikeluarkan UNDP tahun 2003 mengemukakan bahwa Indonesia berada di urutan bawah, yaitu urutan 112 dari 175 negara, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati urutan 58 dan 74, sedang Filipina berada pada urutan 85, bahkan Vietnam menempati urutan 109. Imam Prasodjo berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia sebetulnya sudah masuk kategori “tahap gawat darurat”, salah satu di antaranya karena mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang rendah serta sistem pembelajaran yang tak lagi berkembang akibat krisis sosial yang berkepanjangan.
Pada tahun 2000 ditengarai taraf pendidikan perempuan secara umum jauh lebih rendah dibanding laki
laki sehingga berakibat pada kualitas hidup perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Kesenjangan
gender terkait dengan proses pembelajaran terlihat antara lain pada kurikulum pendidikan yang belum
sepenuhnya terbebas dari netralitas gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari Satuan Kurikulum
Matematika serta Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih ramah kepada anak laki-laki,
sedangkan kurikulum bahasa dan seni lebih ramah kepada anak-anak perempuan. Penulis buku bahan ajar pun tidak responsive gender, karena kenyataannya penulis buku didominasi oleh laki-laki. Profesi guru juga tidak proporsional. Pendidikan dasar didominasi oleh guru perempuan, sedangkan pendidikan menengah dan atas didominasi guru laki-laki. Atas dasar realitas ini maka masalah pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan mendapat perhatian pemerintah, khususnya Kemdiknas. Kemdiknas meresponnya dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Bidang Pendidikan, yang kegiatannya difasilitasi melalui program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan anak unit teknis dan satuan kerja. Pelaksana PUG Bidang Pendidikan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP). PUG Bidang Pendidikan dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut. Tahap sosialisasi dan pengembangan program (2000-2004). Tahap perluasan dan pemeliharaan komitmen (2005-2008). Tahap penguatan dan implementasi (2009-2010).
Yahya Muhaimin mengundang para pembantu, staf ahli, serta kolega-koleganya untuk mengkaji dengan
intensif permasalahan di dunia pendidikan tersebut. Ia datang ke daerah-daerah untuk melihat secara
langsung dan memberi masukan-masukan agar pemasalahan di dunia pendidikan dapat terselesaikan. Ia pun melakukan berbagai program, di antaranya sebagai berikut:
I. Penertiban gelar kesarjanaan dan menertibkan manajemen pengelolaan pendidikan. Pemberian
gelar kesarjanaan, seperti Doktor (S3) serta Magister Manajemen (MM) dan Magister of Business of Arts
(MBA) untuk S2 oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia merupakan program yang illegal dan menghasilkan lulusan bergelar tetapi tidak memiliki kemampuan. Yahya mengatakan, “Di masa krisis seperti sekarang ini, jangan sembarangan mendirikan perguruan tinggi. Karena bila tidak dikelola secara serius, akan merugikan rakyat, yang tadinya ingin menikmati pendidikan di daerahnya sendiri.”
Beasiswa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibat krisis ekonomi, tercatat
37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu pemerintah
membuat Jejaring Pengaman Sosial UPS) untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan
beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) per enam bulan untuk SD/MI/SDLB, SLTP/MTs/
SLTPLB, SMU/MA/SMK/SMLB. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998
berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Biaya hidup menjadi tinggi. Salah
satu biaya hidup yang menjadi beban masyarakat adalah biaya untuk menyekolahkan anak. Pada
saat itu sekolah memungut biaya kepada orang tua, baik biaya rutin seperti SPP maupun biaya
yang bersifat insidental seperti pembelian buku. Biaya yang dituntut dari sekolah kepada orang tua
menjadi beban bagi masyarakat yang tidak mampu.
Anggaran pendidikan 20% dari total APBN sudah ditetapkan dalam undang-undang, namun pada kenyataannya belum terwujud. Untuk itu Yahya berusaha mewujudkan anggaran pendidikan tersebut,
walaupun dalam tataran pelaksanaannya berada di tangan presiden.
Menyusun RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Yahya menyebut lima alasan mengapa
perlu dibuat Undang-Undang Sistem Pendidikan yang baru, yaitu (I) undang-undang (UU)
pendidikan yang sudah ada masih bersifat sentralis, padahal kecenderungan yang sedang
terjadi adalah desentralisasi; (2) UU tersebut tidak merefleksikan pengelolaan pendidikan
yang transparan; (3) pengaruh arus gobalisasi semakin luas dan kuat; (4) potensi masyarakat
harus diberdayakan, baik bagi pengelolaan manajerial maupun dalam pembiayaan pendidikan
yang semakin besar dan kompetitif; serta (5) penertiban gelar-gelar kesarjanaan semakin
mendesak untuk dilakukan.
UU Sisdiknas yang disahkan pada Juni 2003 pada masa Mendikbud Yahya A. Muhaimin menghadapi penolakan dari kalangan nasionalis sekuler dan kaum Kristen, tetapi banyak memperoleh dukungan dari kalangan Muslim. Menurut Busyairi Yahya sejak awal tidak menjadikan agama sebagai isu sentral dalam penyusunan UU tersebut, tetapi pada perkembangan berikutnya mengalami perubahan karena pemerintahan berganti. Penolakan dari kelompok Kristen dan Katholik didasarkan pada anggapan bahwa UU tersebut terlalu mencampuradukkan urusan pribadi dengan urusan publik. Dasar penolakannya adalah Pasal 13 ayat I yang menghendaki setiap siswa diajarkan agama menurut agamanya. Hal itu dinilai
berdampak bahwa sekolah-sekolah Kristen dan Katolik harus menyediakan guru agama Islam jika di sekolah bersangkutan ada siswa beragama Islam. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mempermasalahkan kata-kata taqwa, iman, dan akhlaq mulia dalam UU Sisdiknas tersebut.
Menyelenggarakan pendidikan khusus siswa berbakat. Program ini merupakan upaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan melalui program percepatan belajar siswa atau program
akselerasi. Siswa-siswa yang memiliki bakat bagus dimasukkan ke dalam kelas khusus
dengan jumlah siswa dalam satu kelas hanya sekitar 20 orang, terdiri atas siswa-siswa yang
memiliki kemampuan akademik yang baik. Jam pelajaran ditambah sehingga siswa mampu
menyelesaikan sekolahnya dalam dua tahun dari yang semula tiga tahun. Program akselerasi
diperuntukkan bagi siswa SMP dan SMA. Mereka diberikan mata pelajaran secara intensif:
materi yang lazimnya diberikan dalam enam semester diselasaikan dalam waktu empat
semester. Untuk mengikuti program ini siswa harus mengikuti seleksi ketat. Hanya siswa yang
memiliki kecerdasan tinggi dan berbakat yang dapat lulus dan masuk pada kelas akselerasi.
Menghapus biaya Evaluasi Belajar Tahap Akhir/ Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
(EBTA/EBTANAS). Biaya EBTA/EBTANAS yang menjadi beban orang tua siswa terkadang
memberatkan siswa yang mampu. Untuk menangani permasalahan beban orang tua tersebut
Kementerian Pendidikan Nasional membebaskan biaya EBTA/EBTANAS bagi orang tua.
Biaya tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah.
Membuat proyek jejaring Pengaman Sosial UPS). Kementerian Pendidikan Nasional memperoleh
sebagian dana yang bersumber dari JPS dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa mulai
dari SD, SMP, hingga SMA, serta pemberian DBO atau disebut juga dengan dana (BOS). Pada
tahun 1999/2000 Kementerian Pendidikan Nasional mendapat dana yang bersumber dari JPS
sebesar Rp 775 milyar untuk beasiswa dan Rp 376 milyar untuk DB0.
Program Pembinaan Karakter. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan dari
guru kepada siswa dan siswa bukan hanya sekedar menghafalkan ilmu pengetahuan yang
diterima dari gurunya. Hal yang lebih penting dalam proses pendidikan adalah pembentukan
kepribadian siswa atau pembentukan karakter. Kenakalan yang terjadi pada siswa seperti
tawuran menunjukkan bahwa siswa memiliki karakter yang kurang baik atau sangat buruk.
Karakter yang seperti itu sudah barang tentu tidak mencerminkan makna pendidikan. Untuk
menanggulangi hal tersebut Yahya mengeluarkan program ” Pembinaan Karakter”. Keinginan
tersebut didasarkan atas pengalamannya ketika menjadi dosen Fisipol UGM. Ketika menjadi
Dekan Fisipol UGM ia merasa ada yang kurang baik pada perilaku mahasiswa. Sebagai
contoh, ketika melakukan demonstrasi terkadang mahasiswa menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan prms1p-pnns1p demokrasi, padahal demonstrasi merupakan suatu perilaku untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi tersebut seperti main hakim sendiri yang dapat menjurus pada perilaku anarkis; bahkan dapat mengesampingkan nilai-nilai ketimuran, kepatutan, dan kemanusiaan.
Pelaksanaan program “Pembinaan Karakter” diawali dengan kebijakan menata struktur kelembagaan
birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Yahya mulai melakukan perubahan dengan
menempatkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah koordinasi langsung Sekretariat
Jenderal, baru kemudian menata struktur organisasi dalam rangka pelaksanaan “Pembinaan Karakter”.
Dalam Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Yahya mengatakan,
“Indonesia dikenal memiliki karakter kuat sebelum zaman kemerdekaan, tatkala mencapai kemerdekaan,
dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, karakter masyarakat Indonesia tidak sekuat pada masa
lalu, sangat rapuh. Pemimpin saat ini juga tidak menjaga pembangunan karakter dan budaya bangsa.”
Program “Pembinaan Karakter” baru bisa dilaksanakan pada saat Menteri Pendidikan Nasional dijabat
Muhammad Nuh. Setelah tiga hari Nuh dilantik sebagai Menteri Pendidikan Nasional, Yahya bertemu
dengan Nuh dan menyampaikan program “Pembinaaan Karakter” yang pernah dirintisnya. Nuh
menanggapi dengan baik masukan Yahya dan mengeluarkan kebijakan “Pembinaan Karakter” secara
massal dan harus dilakukan oleh semua sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA, bahkan perguruan
tinggi. Pada masa Nuh kebijakan ini dikenal dengan nama “Pendidikan Karakter” dan menjadi salah satu
dasar penyelanggaraan Kurikulum 2013.
Pentingnya peran IPTEK dalam pembangunan juga tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun
2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas, tahun 2000-2004) melalui empat program
nasional, yang meliputi (I) IPTEK dalam dunia usaha, (2) diseminasi informasi IPTEK, (3) peningkatan
sumber daya IPTEK, dan (4) kemandirian dan keunggulan IPTEK (Zuhal, 2008: 16). Pengembangan,
penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat terjadi dalam suatu
kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan, termasuk sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem
pengetahuan, religi, serta peralatan dan perlengkapan hid up suatu bangsa merupakan faktor yang amat
menentukan apakah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara
efisien dan produktif oleh masyarakatnya

Sumber : Buku ” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018 ” Penerbit Direktorat Sejarah, Direktorat Jendaral Kebudayaan Kemdikbud Tahun 2018